Penulis : Dinda Pranata
Kota Malang di tepi siang cukup panas. Di bawah pohon trembesi aku berteduh dengan buku James Joyce dipangkuan. Gerah. Angin bahkan tak muncul. Mungkin sama malasnya dengan kakiku yang kelu berjalan.
Kubuka halaman pertama buku. Tapi tak kutemukan selain halaman sampul dan daftar isi. Lalu, tanpa basa basi dalam cerita pertama satu kata menahanku.
Kali ini tidak ada harapan lagi baginya: ini strok yang ketiga.
Dubliners 7
Di lembar-lembar awal aku tertahan, meski aku bergerak maju. Apa yang salah denganku? Benarkah suhu siang itu menghalangiku untuk memasuki kota bernama Dublin dan mengenal para dubliners?
Dubliners dan Alinea yang Tak Mengundang
Rumput di taman yang kududuki kali itu lembut. Ujungnya tidak menusuk siapapun yang tergoda untuk menjejalkan diri di atasnya. Meski karpet alam itu menawarkan undangan, tapi suasana tepi siang itu sungguh tak menggugah siapapun terlalu lama duduk. Analogi ini mungkin serupa dengan buku kumpulan cerpen Dubliners karya James Joyces.
Baca juga: Lagu di Radio dalam Perpustakaan Tengah Malam
Cerpen pertama, kedua, ketiga dan seterusnya justru membuatku tak henti berkerut dahi. Di antara pohon trembesi dan rumput taman itu, “apakah pikiranku yang terlalu dangkal mengenali pola-pola ceritanya? ataukah penulis ingin aku menemukan rangkaian titik-titik dari cerita ini?” tanyaku pada akhirnya.
Cerpen kelima buku itu yang berjudul “Setelah Balapan”, ada sesuatu yang merantai pikiranku cukup jauh. Sebuah ironi tentang struktur masyarakat kota Dublin. Dan, mungkin menjadi salah satu yang masih bisa terasa sampai detik aku duduk di bawah pohon trembesi itu.
… orang-orang yang telah melihat begitu banyak dunia dan terkenal memiliki hotel terbesar di Prancis. Orang yang semacam itu (seperti yang disetujui oleh ayahnya) layak untuk dikenal, sekalipun kalau dia bukan teman yang menyenangkan.
Dubliners 46
Jariku mengetuk-ngetuk halaman ke-46 itu. “Aku rasa kota orang-orang Dublin di awal abad ke-20 punya kecenderungan pansos juga,” suaraku lirih. Suatu fenomena yang justru lebih lama dari nama pansos itu sendiri. Aku menggeleng dan menunduk. Melanjutkan baca.
Tapi … cerpen berikutnya seperti pintu yang tertutup. Alineanya seolah menahanku untuk terlalu cepat masuk. Oleh karena itu, aku mencari celah-celah makna, metafora atau simbol yang kukenal. Lalu, kutemukan sebuah ritual yang dekat denganku. Aku menariknya.
Baca juga: Life Lesson, Karena yang Negatif Tak Harus Selalu Positif
Ritual dan Cara Kota Menyembunyikan Diri

Buku setebal 249 halaman sungguh membuatku harus memilih mana pintu yang bisa kumasuki. Lima belas cerpen. Tapi tak sampai setengah dari jumlah cerpen itu, aku bisa merasa buku ini menjaga jarak. “Apa mungkin itu cara pendatang memandang kota Dublin? ataukah memang Dubliner seperti menyembunyikan diri?” Aku bertanya-tanya.
Ketika sampai di halaman 116, Cerpen “Kasus Menyedihkan” membuatku mulai mempertanyakan apa yang disembunyikan di kota Dublin era abad ke-20?
Mr. Duffy sering pergi ke pondok kecil perempuan itu di luar Dublin; sering mereka menghabiskan malam berdua saja.
Dubliners 116
lalu setelahnya di cerpen yang sama …
Dia melihat jejak perilaku perempuan itu yang amoral, menyedihkan dan berbau busuk.
Dubliners 125
Di akhir cerpen ini tak ada kesimpulan pasti, hanya … “Moral tak lebih tinggi dari citra. Dan, Mr. Duffy menunjukkannya.” Ironi atau justru merasa ini adalah ephipani? Aku tidak bisa memutuskannya.
Cerita berikutnya seperti ritual tertutup. Aku berkerut kening mencari simbol ritual yang bisa kupahami. Ada ritual membaca puisi, ada perdebatan dalam sebuah forum, namun cerpen itu tak bisa kupahami seluruhnya. Atau, itu cara James Joyce memberi jarak untuk membaca kota itu?
Lembar-lembar lain kubuka. Sebuah judul cerpen itu membuat tubuh dan kepalaku bereaksi lebih cepat. Di sini mungkin aku bisa menemukan celah-celah untuk mengintip tubuh kota Dublin.
Tubuh dari Kota yang Bercerita
Mr. Holohan mengakui, para artis tidak bagus, tapi Komite telah memutuskan untuk membiarkan tiga konser pertama berjalan sesuka hati mereka dan menyimpan semua bakat terbaik untuk hari Sabtu malam.
Dubliners 154
Cerpen “Seorang Ibu” benar-benar meradangkan tubuhku. Bulu kudukku meremang dan mungkin logika keibuanku bekerja. “Bagaimana budaya hanya dianggap sebagai kata benda, bukan kata kerja,” gumamku setengah mendesis.
Baca juga: Buku Tentang Freud, Kelamin dan Serigala Betina
Cerpen itu benar-benar seperti tangan yang merentang lebar. Isyarat bahwa aku bisa memasuki atau melongok memeriksa tubuh kota itu. Cerpen itu terbaca lebih keras di kepalaku, bagaimana sebuah sistem di era awal abad ke-20 mengerdilkan suara perempuan. Lebih dalam lagi, bagaimana atas nama budaya nasionalisme di Dublin, orang-orang berkepentingan lari dari tanggung jawab: membayar pekerja yang seharusnya.
Dia tidak akan tampil. Dia harus mendapatkan delapan guinea-nya – Mrs. Kearney
Dubliners 161
“Rasanya masuk akal dengan apa yang dilakukan oleh Mrs. Kearney. Jika putrinya tampil namun tidak dibayar,” dengusku. Kali ini aku bisa menarik gambaran kecil dari kehidupan para Dubliners. Yang lebih penting dari itu, sedikit banyak aku bisa melihat gambaran fenomena ini dekat dengan apa yang ada di negaraku.
Dubliners dan Naik Turunnya Pengertian

Tak cukup satu minggu aku membaca buku Dubliners. Adakalanya satu hari bisa dua tiga cerpen, terkadang satu cerpen perlu kubaca dua tiga kali untuk tahu mengapa James Joyce menulis kisah ini. Sering pikiran badung hinggap di kelapa, “apa aku sedang tak fokus sampai tak tahu maksud cerita ini?” Lebih banyak menyalahkan diri.
Malam itu, ketika semua orang sudah berinteraksi dengan alam mimpinya. Lampu bacaku masih menyala. Dua puluh tujuh detik sebelum padam. Halaman 249 itu akhirnya tuntas.
Baca juga: Menyusuri Kios Pasar Sore
Jiwanya berayun perlahan ketika dia mendengar salju jatuh samar-samar di dalam alam semesta dan perlahan jatuh, seperti turunnya ujung terakhir mereka, pada semua yang hidup dan yang mati
Dubliners 249
Dadaku terasa menclos. Mungkin antara rasa tuntas dan tak tuntas. Bisa juga perasaan puas dan tidak puas sekaligus. Aku tak tahu apa nama perasaan di antara itu. Suara tonggeret terdengar dari taman belakang. “Aku ditertawakan tonggeret,” kataku lirih sambil tersenyum nakal.
Dahu yang sering kali kaku dan rambut yang hampir terjabut dari kepala, Buku Dubliners James Joyce seperti kota yang ingin bicara. “Tak apa kalau kau tak paham jalan kota itu, tak apa pula kalau ada cerita-cerita yang tak bisa kau masuki. Itu bukan gagal,” dengung James Joyce dalam kepalaku, “bukankah di kotamu ada bangunan yang memang tak mengizinkanmu masuk, terkecuali kau benar-benar berkepentingan.”
“Lalu jika aku hanya bisa membaca secuil dari maksud tulisanmu, apakah itu artinya aku pembaca yang gagal?”
Sekali lagi tonggeret bernyanyi. Ritmenya sama dengan malam-malam sebelumnya. Lampu baca sudah padam.
Baca juga: Asus AiO V400 dan Panggilan Liar Di Ruang Otopsi
Ada yang sudah baca bukunya atau ada pengalaman nggak baca buku yang ceritanya keluar-masuk seperti ini? Boleh dong berbagi pengalaman seputar proses membacanya, siapa tahu ada orang yang ternyata merasa gagal karena nggak sepenuhnya paham. Tapi tetep ya, dengan bahasa yang santun. Semata-mata biar jejak digital kalian tetap bersih.
Have a nice day!
Jya, mata ne~

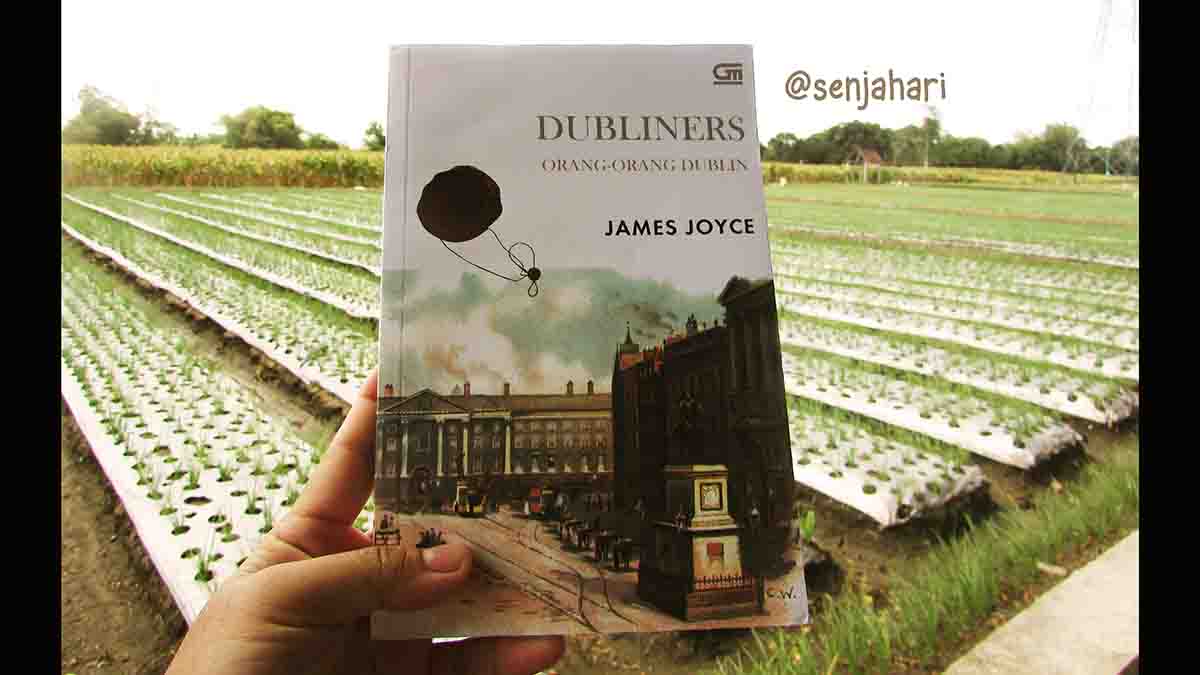





Comment
Dari ulasannya, aku ngerasa James Joyce ini mirip Benny Arnas atau Sasti Gotama, yang cerpennya, kadang perlu dibaca lebih dari 2 kali untuk memahami maksudnya apa, itu pun karena keterbatasanku sebagai pembaca, masih sulit memahami maksud cerpen tersebut dibuat.
Baca buku klasik kayak Dubliner ini emang butuh waktu yang khusus haha, bukan tipe buku yang bisa dibaca sambil nyambi kerjaan lain. Btw, punya akun di goodreads? kalau iya, aku mau follow! 🙂
Aku malah belum baca Sasti Gotama Om. Padahal bukunya ada di lemari masih di plastik pula. Yg judulnya Korpus Uterus itu. 🫣
Kalau Goodreads ada Om, namanya sama: dindapranata
Aku jarang main di sana… 🤭
Ah, memang butuh fokus lebih banyak ya mbak, kalau baca cerita yang kompleks begini. Apalagi, jika tipikal authornya mengajak kita untuk berpikir dan menarik kesimpulan sendiri. Bukan yang memanjakan pembaca dengan kesimpulan atau ending menyenangkan di akhir cerita. Tapi yaa, disitulah seninya, hehehe.
Aku belum lama ini juga pernah baca buku klasik terbitan gramedia. Sekitar halaman kelima puluh, daku tertahan. Kepalaku seperti berasap, lelah menjaga fokus di titik tertinggi, hahaha. Akhirnya sampai sekarang belum lanjut -_-
Kadang buku terjemahan tuh emang cocok²an Mas. Cem cari jodoh.. #aihh 😅
Saya pun pernah baca buku terjemahan (yg katanya gampang) malah nggak nyampe di q. Barangkali ya, saya yg nggak fokus waktu itu .. 🤭
Saya sih belum baca buku ini
Mungkin karena terlalu berat alurnya
Apalagi dengan alur yang tidak biasa
Kapan kapan kita bertemu dan coba membaca buku ini bersama ya Mbak
Pengen dengar langsung intonasi dan semangat mbak menceritakannya padaku
Kadang, ada buku yg mana kita susah utk paham apa isinya. Aku pun sering menemukan buku yg begitu. Dan sama kayak mba, aku juga nanya dalam hati, ini akunya yg bodoh banget sampe ga paham penulis nya mau menyampaikan apa, ataaaau memang bukunya ga bagus, atau hanya utk kalangan tertentu?? Sebel sih, udah mahal2 dibeli, tp ga ngerti 🤣🤣🤣.
Terkadang aku tetep paksa utk baca sampai habis, dengan harapan akan paham di akhir. Ada yg ternyata memang aku akhirnya mengerti, tp ada juga tetep ga paham 😅😅😅.
Malah ada buku yg akhirnya aku nyerah utk baca, saking kesana kesini, ngalor ngidul ga jelas isinya 😅😅. Mana halamannya nyaris 1000 🤣🤣🤣🤣.
Jadi ini cerpen ya mba? Lebih ga cocok buatku. Krn buku yg aku suka, buku yg memang detiiiil alur cerita nya. Jadi tebal gapapa, yg penting memang jelas jalan cerita. Kali cerpen kan selalunya pendek banget, wajar kalau isinya kurang detil. Malah ending suka gantung pula 😅😅.
Tp mungkin ga buku ini kurang menarik Krn terjemahannya yg kurang ? Aku pernah baca buku terjemahan, dan aslinya. Terjemahannya aku ga suka. Feel-nya ga dapat. Diksi ga menarik. Tp buku aslinya aku malah paham dan sukaaa
Huaaa, 1000 halaman. Jadi inget satu penulis luar bukunya setebal kamus. 🤣
Kadang cari buku terjemahan tuh kayak cari jodoh Mbak Fan. Ada yang terjemahan bagus, tapi nggak cocok di kita. Begitu sebalilnya. Ya jd sebel juga akhirnya.. Apalagi kan mahal² beli.. 🫣
Saya sangat jarang membaca buku dari penulis luar, Mbak Dinda. Apalagi kalau bahasanya berat. Terus terkadang baku dan kaku, karena hasil terjamahan.
Saya suka yang bahasanya ringan, jadi walau konfliknya berat, mudah dipahami. Apalagi untuk sebuah cerpen. Itu kan, ceritanyanya tidak terlalu panjang dan bisa selesai dibaca dengan sekali duduk. Tapi kalau kumpulan cerpen dan banyak ceritanya membuat kening berkerut, saya biasanya tidak lanjut membaca bukunya dan beralih ke buku yang lain hehehe.
Nggak semua cerpen bisa langsung kita pahami dalam sekali baca. Ada memang cerpen yang kudu dibaca dua atau tiga kali baru kita menemukan maksudnya. Mungkin Dubliner juga begitu.
Ooh ini kumpulan cerpen ya? Kirain novel. Belum pernah nih baca karya James Joyce. Jadi penasaran.
Btw Mbak Dinda lagi suka baca karya sastra klasik?
Kalau susah bacanya, coba cari English version aja. Sorry to say, biasanya lebih baik yg ori daripada terjemahan.
Kalau buku cerita yang alurnya kompleks seperti ini, kerap kali nggak daku pilih, karena takut dakunya galfok. Lebih suka yang fokus dengan cerita yang ada, dan misalnya mau dibuat unik itu ada plot twist nya, nah ini mantul deh
Aku belum membacanya bukunya dan menjadi penasaran untuk membacanya. Seperti panggilan khusus, ada apa dengan karya James Joyce ini.
Kalau soal membaca yang kadang tidak di mengerti, aku sering mengalaminya. Hanya aku teruskan saja membacanya, tanpa sadar di akhir baca ada gambaran utuh yang terpahami. Serunya membaca buku buatku itu, kadang saat baca tidak paham tetapi seiring waktu saat mengalami sesuatu yang berhubungan dengan tulisan yang dibaca, suka teringat dan jadinya mengerti. Kadang disitulah aku semakin menyukai kerja logika dan sungguh luar biasa karya pencipta.
Anw, tambah nih refrensi buku yang jadi list di 2026. Tulisanmu sungguh racun Dinda wkwkwwk
Samaaa mbak.. Saya juga tetep kubaca, alasannya karena sayang buang uang buat beli bukunya. Apalagi tebel harganya lumayan mahal. Tapi setelahnya kutandai siapa penerjemahnya, which is besok kalau beli buku dari penerjemahnya kudu siapin batin dulu. 🤭
Ini kumpulan cerita gitu ya mbak? Aku belum pernah baca. Kayanya bahasanya atau ceritanya berat ya. Jadi beberapa cerita butuh dibaca berkali-kali biar bener-bener paham. Harus fokus ya kalau baca buku tipe begini.
Ada beberapa buku yang memang isinya lumayan bikin kening berkerut yaa dan biasanya itu buku sastra. Aku jujur belum ada bayangan sih apa aja yang diceritakan di kumcer ini namun pastinya menarik mengetahui kehidupan warga dublin di abad lampau
Tulisan ini menangkap esensi Joyce dengan jujur, kak. Ceritanya memang nggak menawarkan hiburan instan, tapi justru mengajak kita berhenti dan merenung tentang hidup sehari-hari yang sering terasa biasa, namun sarat kegelisahan. Tema paralisis, pilihan yang tak pernah diambil, dan emosi yang terpendam terasa dekat, meski dibungkus dengan gaya yang dingin dan subtil. Dubliners memang bukan bacaan santai, tapi justru di situlah kekuatannya, membuat kita pulang dengan pertanyaan, bukan jawaban.
Ternyata buku ini terbitan Gramed ya. Aku belum pernah baca buku kumpulan cerpen Dubliners karya James Joyces. Malah baru tau karena baca artikel mba.
Akan tetapi, membaca buku sejenis ini, sulit ditangkap dan alurnya rumit serta sering tak ada kepastian di dalam nya. Bikin merenung, mikir dan pusing sendiri 😭😭😭
Bukan pembaca yang gagal seharunya. Memang butuh waktu lebih buat memahami satu persatu cerpennya. Kebayang ada suara tonggeret enakeun merdu walau di beberapa part berasa kayak lagi ngeledek.
Hehehe… Malah kadang tonggeretnya jadi lebih enak di denger ya mbak daripada bacaannya. Kata kawanku: distraksi muluk kalau baca. 🤭
Wah ini adalah sebuah cerita yang pasti menarik bagi orang yang memang suka dengan penelusuran pemikiran sehingga bisa mengasah otaknya untuk mencari tahu dan lebih memahami ceritanya tapi mungkin buat orang-orang yang suka cerita yang ringan mungkin kurang cocok ya Tapi harusnya dijadikan tantangan supaya bisa menjadi peluang untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang berbeda dibandingkan yang biasa dibaca
ceritanya memang penuh intrik , isinya menceritakann sisi kota dublin dari kelas bawah smpai kelas atas.
Abad 20 ada pansos duh aku salfok sama kata2 itu ,
salut sama tth seslalu konsisten baca novel
Wow banyak yaaa, 15 cerpen dalam satu buku 😀
Wah wah ada apa dengan masyarakat Dublin nih? Kalau aku membayangkannya mereka tu kaya akan landmark2 peninggalan kerajaan Eropa gitu nggak sih mbak? trus perpaduan Inggris-Irlandia, orang2 yang sudah sepuh dan ramah hehe.
Ini pengarangnya mungkin idenya sedikit banyak bersumber dari itu yaa. Nggak mudah lho nulis 15 cerpen, apalagi yang bisa dibaca dengan pilihan tanpa harus runut 😀
Mungkin emang tipe cerpennya nggak bisa maksa buat baca cepat, sehingga nggaka da masalah dapat satu dua cerpen terus berhenti kali ya?
Aku sendiri kalau baca buku kumcer suka gitu, apalagi kalau bahasanya terlalu sastra banget gitu, apalagi terjemahan, mungkin butuh waktu lebih lama.
Dulu saya beli ini karena kata Dublin itu mbak. Maafkeun inget westlife. Boy band dari sono.. hihihi.. 🤭
Kiranya saya bisa dapat cerita menarik atau setidaknya gambaran cakep kotanya. Malah dapet pusing. Tapi ya seru juga, krn jarang saya baca cerpen tentang kota.. 😍😍
Saya pribadi kalau kesan pertama bukunya udah sulit dicerna dan dipahami biasanya gak dilanjut bacanya Mba. Kadang kepala berasa ngebul dengan bacaan yang membuat gagal paham. Lebih senang baca tulisan yang ringan meskipun isinya berat.
Aku belum pernah baca buku ini
Tapi dari review mbak Dinda ini, sangat terlihat jika buku ini berisi cerita cerita yang menarik dan seru
Walau kadang harus dinikmati secara perlahan ya mbak
Wow.
Agaaa.. sulit untuk memilah satu crita yang sesuai dan menyelami karakternya yaah..
Tapi beneran jadi tau kalau ada penulis yang membuat bukunya menarik dengan tidak mengikuti tema-tema yang sedang ‘tren’.
Buku Dubliners kudu banyak fokus dan mencerna sejenak dalam diam.
Ulasan Dubliner ini menarik karena menyoroti potongan kehidupan sehari-hari yang sederhana, tapi sarat makna dan refleksi sosial.
Suka gaya ulasannya! Memang baca buku klasik itu kayak masuk labirin, kadang tersesat tapi selalu ada makna yang tertinggal di hati.
Temukanlah satu buku dan jatuh cintalah dengan buku tersebut. Sebuah pepatah yang selalu bergema di ingatan saya. Jika saya amati buku yang dipilih mbak ini kategorinya berat0berat termasuk Dubliner kali ini. Tapi saya suka cara mengulasnya membuat saya jadi ikut mikir nih
Baca ulasan ini, jadi teringat kumpulan cerpen The Coffee Shop Chronicles. Semua cerita mengambil lokasi di satu kafe dengan berbagai sudut pandang. Dubliners kaya gitu ya. Terus jadi pengen lihat keindahan Dublin juga deh
Aku agak sulit memahami tentang review dari kumpulan cerpen karya James Joyce ini. Sehingga, aku merasa kalau ini bukan jenis bacaan yang akan kusukai.
jadi dari buku Dubliners, kita bisa dapat gambaran peristiwa yang dialami masyarakat Dublin di abad 20-an yang disajikan dalam beberapa cerpen, sepertinya menarik…
Bukunya menarik sekali untuk dibaca, salut dengan orang-orang yang membaca buku seperti ini yang membutuhkan banyak sekali konsentrasi karena alurnya yang komplek.
Wah ada banyak cerita yang belum saya baca ternyata. Berkiprah di ranah praktis dan kecenderungan mengejar akademik selama ini membuat saya absen dari buku fiksi. Wajib punya nih. Soalnya belakangan mulai tertarik menulis fiksi.
Daku belum baca bukunya Kak.
Sepertinya kakau hendak baca ini, buat daku nggak bisa sekali duduk, karena gaya bahasanya agak berat buat dicerna, dan perlu fokus yang pas. Setidaknya ulasan kak Dinda ada gambarannya buat daku
Kadang saya juga gak bisa selesai seminggu membaca buku kalau setiap bab memiliki cerita yg berbeda. Perlu mencernanya dulu
Padahal hanya 249 halaman ya
Sementara novel lain yang sampai 600 halaman bisa menyelesaikan tamat dalam waktu tiga hari saja.
Alur dan kisah yg rumit beneran memerlukan ruang dan waktu sehingga kita bisa menjadi bagiannya. Bukan asal baca lalu gak ngeh ini maksudnya apa?
Jadi penasaran sama isi bukunya kak. Thanks, jadi punya list buku baru untuk dibaca
Saya belum baca buku ini mba…kalau saya buku kumpulan cerpen yang menarik itu ada judulnya sepasang sepatu tua menurut sqya sih seru juga, para tokoh utamanya adalah benda² mati.
Kalau membaca sekilas… aku jadi teringat banyaknya tiktokers yang tinggal di Eropa dengan menceritakan kehidupan mereka. Mungkin kurang lebih begitu gambaran Buku Dubliners James Joyce ini ya..
Menarik sekali menurutku membaca kumpulan cerpen yang bercerita tentang kehidupan di sebuah kota dan menggambarkan bagaimana perilaku warga kota tersebut. Pastinya memberikan perspektif baru bagi kita
39 Responses