Penulis : Dinda Pranata
Aku hanya mendengar kalimat menyayat yang sama. Seorang wanita muda dengan latar reruntuhan bangunan, “aku ingin mereka memanusiakan manusia,” katanya. Suaranya menyusup ke arahku, si telinga.
Aku, si mata, tertarik melihat kerutan dahi wanita muda itu. Penuh sorot amarah. Meski angle amarahnya selalu sama yaitu menyoroti ketidakadilan penggusuran itu.
Lagi-lagi si telinga dan si mata berdebat. Sekali lagi ibu jariku maju mundur di atas layar, tak tahu apa yang harus aku lakukan. Sementara itu, informasi jadi masuk sepotong-sepotong.
Sirkuit otak mulai kacau. Ada terintervensi halus yang tiba-tiba datang. Hati. Ia akhirnya mengambil alih segalanya. Aku belum sempat berpikir jernih, tapi ibu jariku bergerak cepat mengikuti intervensi hati. Terkirim.
Aku terdiam lama. Sampai aku sadar, responku ini bukan sekedar tak sadar diri.
Yang Berdebat Tiga Suara, Yang Ditafsir Ribuan Makna
“Kau kan sudah sering melihat ini. Mengapa masih saja kau nikmati!” seru telinga. Kesal.
Baca juga: Adarusa Marah, Pemberi Utang Resah
“Aku juga tak tahu. Meski sudah sering melihat gadis itu wira-wiri talkshow, tetap saja memantik rasa penasaranku,” sahut si mata yang sama-sama kesal.
“Sadar nggak sih kau itu?! hati sudah memanipulasimu!” seru telinga. Gemas.
Pelan-pelan ada sensasi lain muncul di ulu hati. Ia merangkak naik ke dada dan berusaha keluar dengan menggedor jantung. Dag dig dug!
“Wah, kalian kenapa nyalahin aku sih? Kan aku cuma ngerasa saja, apa yang mata lihat dan telinga dengar. Lagipula, aku juga kasihan sama gadis itu,” sahutnya lirih. Hati meremas jantung. Sentimentil.
“Ya kalau kamu nggak dateng. Dia nggak akan memencet like!” seru mata dan telinga bersamaan.
Baca juga: Satu Kotak Harapan, Isinya Kejutan yang Tak Diharapkan
Aku ini hanya penonton. Tapi, yang ramai justru organ-organku. Gelisah.
“Mungkin ini yang terjadi pada Stuart Hall waktu merumuskan teori representasi ya?” tanyaku pada akhirnya.
Hati, telinga dan mata terdiam. Mereka seperti menungguku berbicara. “Ketika aku bertemu dengannya, dia menyampaikan bahwa makna itu dibangun oleh budaya dan bisa berubah tergantung penyampai berita dan penerimanya,” kataku.
“Apa yang dia bicarakan? Serius aku nggak ngerti,” tanya hati yang memberi isyarat lewat syaraf-syarat yang menegang di sekitar perutku. Mata dan telinga meminta si hati tak berisik.
Aku tertawa mendengar organ-organku. “Aku yakin kalian pasti bingung,” tawanya. “Saat itu aku bertemu dengannya di lembaran-lembaran menguning dalam gudang. Berangkat dari pemikiran Stuart, aku tidak menyalahkan gadis itu jika ia viral. Ada campur tangan media (produsen) yang terus mengarahkan kamera, audiens (decoding) yang menerima berita, proses pemaknaan audiens (representasi) sampai hasil akhir berupa pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada gadis itu.”
Baca juga: Logika Jungkir Balik Khas Warga Komplek
Mata, telinga dan hati terdiam. Merenung. Pelan-pelan sesuatu tersibak. Seperti gorden yang perlahan terbuka. Mata, telinga dan hati tahu ada sosok lain yang seringkali terlupa di saat seperti ini.
Eksploitasi Emosi: Hati yang Baperan, Bisa Jadi Korban

“Kalian ini ribut sekali!” serunya. Si Akal tampaknya baru bangun dari tidur panjangnya.
“Kemana aja sih!” seru mata dan telinga. Jengkel. “Kau kan harusnya standby dong! malah molor!” seru telinga.
“Bukan molor, cuma lagi bongkar-bongkar gudang memori. Penuh,” sahutnya, “kalau aku tidur, dia nggak akan ingat ada yang namanya Stuart Hall. Kali ini aku mau ngingetin dia sama satu orang lagi, namanya Arlie Russell Hochschild.”
“Aku pergi aja ya! Kalian sudah ada si akal. Aku udah nggak dibutuhin lagi,” ujar Hati lirih. Ia berdesir pelan di jantung. Sentimentil lagi.
Baca juga: Ekologiverse Versi Irfan Yuta Pratama di Dunia Kedua
“Eh, jangan dong! Kamu juga perlu tahu si Arlie ini. Kalau kamu nggak tahu, nanti kamu malah jadi korban berikutnya,” cegah si akal. Kali ini hati tersenyum. Sisi perasanya meremang. Merasa diperhatikan.
Aku yang merasakan ke empat organ ini merasa absurd dan hanya bisa geleng kepala. Tapi, ketika si akal mengingatkanku pada nama Arlie, aku mulai bisa menyambungkan benang merah fenomena gadis itu.
“Ketika representasi Stuart Hall bilang kalau (media) produsen mendramatisasi berita gadis ini condong ke satu sisi, maka persepsi audiens bisa tergiring ke sisi tersebut. Lalu, emosi penonton berhasil tergiring, media melihatnya sebagai peluang: likes, views, dan undangan acara berikutnya. Eksploitasi emosi. Emosi berubah jadi angka. Dan angka jadi panggung yang terus meluas.” kataku, “Arlie Russell Hochschild menyebutnya komodifikasi emosi.”
Rupanya mata, telinga dan hati terdiam sejenak. “jadi orang lain bisa mengaturku dengan sengaja dengan eksploitasi emosi ini,” kata hati dengan nada rendah. Sedih.
“Astaga! Kok kamu baru sadar,” kata mereka bertiga serempak. Si mata membelalak, si telinga memerah dan si akal cuma bisa geleng-geleng.
Baca juga: Asal Kata Toast yang Bikin Istri-istri Pada Ngambek!
“Jika kamu sadar eksploitasi emosi itu, aku beri tahu bahwa Arlie menyebutnya emotional labor atau usaha mengatur perasaan dan ekspresi emosi agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau situasi sosial,” kata akal sambil membelai lembut hati.
Invitasi dan Diskusi
Aku mengikuti diskusi mereka dan tersenyum. Aku menatap dan mendengar suara yang sama di podcast lain, tapi kali ini bukan karena iba atau marah. “Apa kau merasakan yang sama?” tanya akal padaku, pada hati, mata dan telinga.
Namun, untuk pertama kalinya satu pertanyaan terucap bersamaan, “bagaimana dengan perasaan gadis itu sendiri?”
Itu yang membuat kami gamang. Mata menatap gadis itu, telinga menyerap semua kata-kata gadis itu, hati merasakan resonansi emosi gadis itu dan akal memproses nasihat-nasihat pembicara di media. “Gadis itu mungkin belum sempat merenungkan apa yang sudah ia lakukan,” kataku kemudian.
Gimana menurutmu nih gengs? ada yang ngikuti fenomena ‘si gadis’ ini nggak? Eits, jangan baper dulu ya, coba baca pelan-pelan. Kalau siap boleh dong berbagi pendapat di kolom komentar. Namun, perhatikan tutur kata juga ya, semata-mata biar jejak digital kalian tetap bersih.
Happy Sunday, Jya mata ne~~
Source:
Wharton, Amy S. “The Sociology of Emotional Labor.” Annual Review of Sociology, no. 1, Annual Reviews, Aug. 2009, pp. 147–65.
https://tirto.id/mengungkap-topeng-empati-yang-jadi-senjata-eksploitasi-emosi-hcDk
https://easysociology.com/sociology-of-emotion/arlie-hochschilds-theory-of-emotion/
https://bandung.kompas.com/read/2025/04/28/115058478/debat-dengan-aura-cinta-soal-perpisahan-sekolah-dedi-mulyadi-anda-miskin




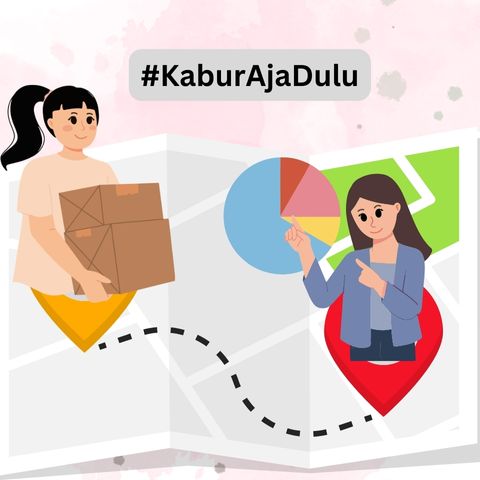


Comment
Hmmm jadi begitu ya.. kayanya sih simpati. Tapi agak sedikit emosian nih 😁😁
Pernah ngerasa juga sih, kadang simpati itu ujung-ujungnya dimanfaatkan. Pengalaman yng udah udah bikin aku jadi lebih peka dan mikir dua kali sebelum bereaksi.
Sepertinya lebih mendekati emosi dibandingkan dengan simpati. Cuma dilabelkan dengan simpati. Tapi banyak yang tidak mau mengaku bahwa itu adalah emosi.
Mungkin simpati, tetapi jika tahu rasasimpati itu dimanfaatkan jadi berujung emosi. Namun, entahlah masih gamang juga beda tpisi nih antara simpati dan okploitasi emosi
Aku sedih. Kasian banget menurutku. Karena si gadis kecil ini sebenarnya nggak paham konteks pembiacaraannya, dia bahkan seperti ‘dimanfaatkan’ banyak pihak, media terutama. Tapi dia nggak sadar. Andai aku jadi orangtuanya, aku stop kasih izin dia wara wiri kemana-mana. Kasian mentalnya. Aku bukan ortunya aja sedih, tp tampaknya dia menikmatinya. Nggak Tau jg.
Ini adalah kondisi yang kadang saya saya rasakan. Misalnya saat melihat postingan ibu-ibu muda yang memposting penderitaan jadi seorang ibu. Entah karena punya anak banyak dengan jarak berdekatan, yang mengeluhkan susahnya tinggal bersama mertua, atau ada yang menyampaikan negatif feeling menjadi ibu yang iri dengan rutinitas suaminya yang tidak berubah meskipun sudah punya anak. Sedangkan si ibu harus terpaksa berhenti kerja, ga punya teman, dan ga ada waktu bahkan untuk menghibur diri sendiri.
Tepatnya sih, rasa simpati sekaligus emosi karena “itu adalah pilihan dia” “itu merupakan suatu kondisi yang sebenarnya bisa diusahakan” tapi kenapa si ibu ga mampu mencari solusi. Sekalinya diberi solusi, ada beribu alasan.
Misalnya, ibu yang banyak anak menderita, dikasih saran untuk KB, atau suaminya yang KB jika gagal di istri, tetap saja dilawan dengan alasan ini dan itu. Begitu juga ibu yang punya bayi dan masih tinggal dengan mertua, itu memang pahit. Di sini lain mungkin dia tidak berdaya, tak merencanakan itu, tapi tetap saya emosi. Entah kenapa melihat keadaan seperti itu rasanya antara simpati dan emosi. “Kenapa ga lari aja, atau gimana?”
Beberapa teman bercerita, memang ada orang-orang yang seperti ini mbak Im.
kadang mereka itu cuma mau ngeluh atau ngeluarin uneg-unge, cuma ngeluhnya (mungkin) tidak di situasi yang pas dari pendengarnya.
Jurus jitu teman saya malah cukup bilang, “saya ikut prihatin”, atau semacamnya biar ngeluhnya nggak terlalu panjang. 😀
Dari awal menyimak berita si gadis ini langsung emosi, sih, padahal saya bukan orang yang sering pro pemerintah. Namun, makin ke sini makin timbul kesadaran, kemungkinan ada pihak-pihak di balik layar yang membuat ini semua jadi huru-hara. Kecil kemungkinan si gadis berdiri sendiri.
Meski blm faham gadis kecil mana yg dimaksud (jadi penasaran deh..)…tapi aku suka dg cara bertutur tulisan ini. Runtut dan membuka wawasan. Terima kasih yaa…
Pembahasan soal eksploitasi emosi lewat sudut pandang organ tubuh bikin topik berat jadi lebih mudah dicerna. Setuju banget kalau kita perlu lebih sadar bahwa emosi bisa dimanipulasi dan dijadikan komoditas, apalagi di era media sekarang.
Kadang percakapan yang terjadi antara 4 indra ini sering terjadi dunia politik dan dunia kerja. Seperti kita tau semua hal yg menurut kita itu benar, pun saat kita tau dan dengar dari sisi yg berbeda pastinya emosi dan marah ya kita respon. Tapi di satu sisi, kita tau posisi kerja yg bikin empati kita berkurang, ya pada akhirnya kita dilabeli manusia yg tak pandai memanusiakan manusia.
Tapi salutnya, banyak juga mereka yg mendahulukan emosi dan empati diutamakan tanpa mereka abaikan posisi kerja mereka. Dan bisa memanusiakan manusia juga, ini baru keren!
Kadang percakapan yang terjadi antara 4 indra ini sering terjadi dunia politik dan dunia kerja. Seperti kita tau semua hal yg menurut kita itu benar, pun saat kita tau dan dengar dari sisi yg berbeda pastinya emosi dan marah ya kita respon. Tapi di satu sisi, kita tau posisi kerja yg bikin empati kita berkurang, ya pada akhirnya kita dilabeli manusia yg tak pandai memanusiakan manusia.
Tapi salutnya, banyak juga mereka yg mendahulukan emosi dan empati diutamakan tanpa mereka abaikan posisi kerja mereka. Dan bisa memanusiakan manusia juga, ini baru keren!!
Aku pertama kali lihat si gadis ini juga langsung emosi, wkwk. Pasalnya kayak “paham konteks nggak sih?” Bagus sih berani menyampaikan pendapat, tapi rasanya dia juga harus banyak belajar literasi. Dia sendiri pun menyampaikan dengan penuh emosi. Seharusnya nggak usah dikasih panggung, tapi ya banyak yang kepo kayaknya jadi pengen lihat si gadis muda ini lebih jauh, huhu.
Hehehe, terkadang saya sih yg kek gitu. Gak pakek mikir lagi. Harus memperbaiki
Hehehe langsung kebayang ini tentang siapa dan apa mba. Sedih sih, jadi kayak dieksploitasi, tapi bingung juga ketika si anak juga nggak mencoba belajar mencerna. Apa karna masih polos atau memang dia tidak mau tahu juga? Heheh entahlah
Jangan terlalu simpati apalagi jadi orang yang gak enakan, karena acap kali jadi sarang dimanfaatkan orang² gak baik
Ihhh pas baca langsung “paham konteks ga sih” haha mungkin awalnya simpati, tetapi berakhir jadi emosi yaa..
Aku uda mulai menghindari banget untuk tau masalah orang. Karena aku orangnya gampang kepengaruh. Awalnya pasti ngerasa simpati yaa.. tapi kalau baca kolom komentar, kadang kegocek juga tuh..
Makanya bahaya banget terlalu tau masalah orang lain.
Meski ada ibrohnya, seperti kita bisa belajar dari permasalah oranglain, tapi kalau lagi labil, malah ketikannya uncontrol… ((istighfaarr, istighfaar))
Di dalam dunia entertainment ataupun media, cara-cara eksploitasi emosi penonton ini, bisa dibilang jadi cara ampuh untuk mereka menaikkan cuan. Saya bisa mengatakan ini karena acara TV seringkali mengundang kedua belah pihak yang jelas tidak berimbang secara keilmuan untuk menaikkan ratings.
Hmm, beda tipis ya
Sepertinya aku seringnya sampati tapi sambil emosi juga
Haha
Jadi belajar kosakata baru nih setelah membaca cerita nya mba Dinda…emotional labour….jadi belajar lagi tentang psikologi.
Memang skrng kita itu tidak boleh simpati berlebihan ya. Karena ujungnya orang lain bisa memanfaatkan. Misal punya teman yang sering menceritakan kisah sedih, mending kita skip saja bahas hal lain karena kalau kita simpati bisa dimanfaatkan
22 Responses