Penulis : Dinda Pranata
Kadang aku berpikir, apakah kita harus mendengar rasa sakit yang terus dirayakan? Entah lewat percakapan sederhana atau lewat tayangan televisi yang menelanjangi luka.
Saat itu, aku berdiri di bawah kaki dua wanita di bawah pohon mangga. Sesekali radar merah di atas kepalaku bergoyang, menyerap suara seperti telinga, sambil berusaha mengambil secuil dedaunan jatuh yang masih menyimpan rasa manis.
“Itu bukan seberapa, Bu! Saya dulu pernah rugi ratusan juta, mana lagi waktu itu anak mau masuk SMP. Deritanya jadi double,” kata salah satu wanita berambut keriting itu.
Seolah tak mau kalah. “Zaman saya juga lebih susah, Bu! Bayangkan, saat COVID-19. Suami di PHK, usaha rugi, anak sakit dan kemudian, dia harus dapat perawatan medis. Susah sekali, Bu,” jawab wanita berbaju hijau lumut di sampingnya.
Dengan tangan kurus dan tipis, aku menatap kedua wanita itu. Tertegun. Aku berhati-hati menyingkir. Bukan karena takut, tapi karena aku membawa lebih dari sekedar dedaunan kering.
Baca juga: Yang Dilihat Postingan, Yang Dihakimi Kehidupan
Luka dan Identitas Sosial
Aku berjalan memegangi daun yang nyaris terbawa angin. Kadangkala, tubuhku yang kecil ini terhempas angin yang kasat mata. Menderita? Tentu saja. Semua spesiesku pasti pernah mengalami hal yang sama.
Sepanjang perjalanan, aku mengamati lipan kecil menggeliat di tanah. Lalu cacing merah yang bekerja keras menggemburkan tanah. Mereka menderita. Nyaris terluka dalam hidupnya. Meksi begitu, mereka memilih hening? Tidak seperti manusia, yang memandang luka sebagai ajang gembar-gembor.
Berbeda saat aku di bawah pohon mangga itu. Aku menemukan hal tak biasa. Bagi manusia, luka bisa menjadi sebuah ajang lomba. Siapa yang paling menderita, dia pemenangnya. Terkejut. “Kukira mereka berbagi luka untuk menenangkan, ternyata ….” aku terhenti. Ragu meneruskannya.
Setelah itu, aku merayap di atas pohon mangga. Ke dahan yang tak terlalu tinggi, meneguk getah pohon yang manisnya luar biasa. Haus. Angin datang lagi. Tak kencang. Tapi, cukup membuatku nyaris terpeleset jika daun pohon mangga tak menahan angin itu. “Terima kasih,” kataku pada pohon itu.
“Itu bukan masalah,” jawabnya dengan suara bass, yang hanya bisa kudengar, “kau pasti heran, semut kecil. Mengapa kedua wanita itu bisa berlomba menjadi yang paling menderita,” tebak pohon mangga. Aku tersenyum.
Baca juga: Jika Malin Kundang Tak Durhaka, Akankan Citranya Berubah?
Pohon mangga yang cukup tua itu, tertawa pelan. “Foucault bilang itu adalah diskursus. Ya, semacam cara manusia memahami dan memaknai dunianya,” jelas pohon itu.
“Siapa Foucault dan apa hubungannya dengan manusia yang berlomba menjadi terluka?” tanyaku.
“Foucault juga manusia. Bule dari Prancis yang sudah wafat puluhan tahun lalu. Dalam diskursus atau wacana itu, ada aturan tak terlihat yang menentukan posisi seseorang di mata dunia sosial manusia.”
“Jadi aturannya, yang paling menderita dia yang menang?” tanyaku memvalidasi.
Si pohon menggoyangkan dahannya pelan. Mengangguk. “Contohnya seperti dua ibu tadi. Mereka berlomba menjadi ibu paling menderita, agar orang memberikan tepuk tangan dan memberi label “si ibu hebat”, “si ibu sabar”, “si ibu panutan”,” sahutnya lagi.
Baca juga: Mengapa Kita Takut Tak Menjadi Siapa-siapa?
Kemudian radar di kepalaku menegang. Terkejut.
Diamnya Luka, Apa yang Tersisa?

“Beberapa manusia lebih drama dari manusia di zaman batu. Kalau si luka bisa berbicara mungkin dia akan bersorak karena orang memperebutkannya,” canda si pohon. Aku tertawa kecil, meskipun sebenarnya pikiranku tak sepenuhnya mengerti.
“Apa ada orang memilih menyimpan luka daripada mempertontonkannya?” tanyaku lagi.
“Ada! Dan jika kau beruntung, kau akan bertemu dengannya,” kata pohon tua itu lembut, sebelum aku pamit turun.
Beberapa saat kemudian, tanah bergetar. Kukira gempa. Ternyata seorang wanita berjalan melewatiku. Berteduh di bawah pohon mangga. Kali ini hanya seorang. Duduk diam. Wajahnya tirus, dan matanya … “dia bersedih,” kataku pelan.
Baca juga: Logika Jungkir Balik Khas Warga Komplek
Wanita berbaju kuning duduk diam. Mungkin inilah yang dimaksud oleh si pohon
“Woi! Minggir! jangan halangi jalan!” seru cacing tanah yang membuatku nyaris jatuh ke belakang.
“Maaf,” kataku sambil memberinya jalan. Cacing tanah itu melihatku menatap wanita itu cukup lama. Terpana. “Jatuh cinta?” tanyanya sambil tersenyum geli, “sayang, wanita itu selalu menunggu suaminya yang tak pernah pulang.”
Aku terdiam.
“Dia mirip Victor Frankl,” kata cacing lagi.
Baca juga: Diskusi Sehat Bubar, Anggota Barbar
“Siapa itu? Sepertinya laki-laki?” tanyaku penasaran. Cacing mengangguk.
“Rupanya tidak banyak yang mengenal pria itu. Seorang psikiater. Satu yang aku ingat tentangnya adalah bagaimana ia mendapatkan makna di setiap lukanya.”
“Apa maksudnya?”
“Jika kau terluka, bukan seberapa dalam luka derita yang kau terima. Tapi, bagaimana caramu merespon luka itu,” kata cacing. Mata kecil cacing menatap wanita itu. Ia hanya menatap langit. Seolah meminta hujan sebagai pengganti air matanya.
“Andai ia masih hidup, mungkin akan berkata begini pada orang yang berlomba memamerkan luka. ‘Sia-sia kau memamerkan penderitaanmu, jika akhirnya kau akan mengulangi penyebab luka itu’,” kata cacing sambil menggeleng. Hening.
“Nah, aku harus pergi,” pamitnya lagi. Lalu, menggali tanah dengan tubuhnya.
Iba. Diam-diam aku mengamati wanita itu. Meskipun dia duduk sunyi di bawah pohon itu, entah mengapa senyap sedihnya sampai padaku. Terenyuh.
Invitasi dan Diskusi
Semut pulang ke sarang membawa tak hanya barang, tapi juga cerita yang tak bisa ia timbang. “Barangkali, dunia sudah lama berubah dan aku tidak menyadari itu,” kata si semut, “sekarang, luka dan identitas sosial seolah tak terpisahkan bagi manusia.”
Ia duduk di atas bongkahan batu kecil di dekat sarangnya. “Mengapa rasanya untuk hidup di jaman sekarang terasa melelahkan? Ketika luka dan identitas sosial, menjadi cara agar manusia bisa mendapat makna dengan cepat.”
Aku mendesah. “Kadang aku berpikir, bagaimana perasaan luka ketika ia dipamerkan saat ia ingin begitu intim dengan manusia? Salahkah aku berpikir seperti itu?” tanyaku lagi.
“Ah, aku hanya semut. Makhluk kerdil yang tak tahu apa-apa di dunia yang luas ini,” kataku dan beranjak turun dari batu.
Gimana nih gengs, pernah nggak punya pengalaman mau curhat sama orang malah jadi adu siapa yang paling menderita? Nah, setelah baca narasi tadi apa nih pendapatmu? Kalian boleh berbagi ya di kolom komentar. Eits! Tetap dong bahasanya dijaga ya, biar jejak digital kalian tetap bersih.
Happy Tuesday!
Source:
Kurniawan, R., & Zubaidah. (2023). Konsep diskursus dalam karya Michel Foucault. Jurnal Filsafat Indonesia, 6(1), 21–28
Sumanto. (2006). Kajian psikologis kebermaknaan hidup. Buletin Psikologi, 14(2), 115–130. ISSN 0854-7108.



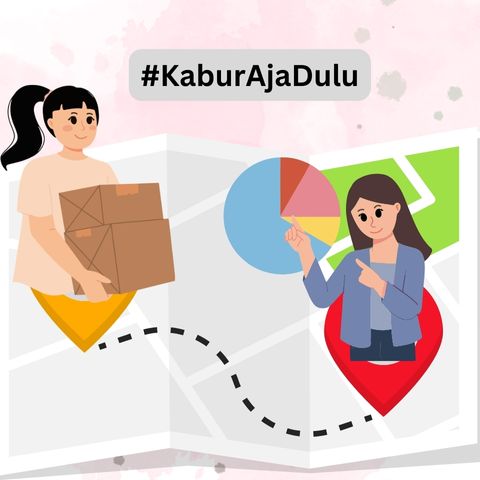



Comment
Sedikit tertampar baca ini. Aku jadi mikir apakah pernah melakukan tanding-tandingan luka semacam itu? aku sih sadar betul kalau ada yang lagi curhat sebetulnya alih-alih mendengar tanggapan yang serius mereka tuh cuma butuh kuping. Butuh didengarkan.
Tapi ya, di beberapa kesempatan aku masih mempraktikkan tanding-tandingan luka ini >.< terutama kalau yang curhat udah muncul sinyal-sinyal mau melimpahkan kesialan/luka mereka terhadapku. Jadi ya, kayak bikin perisai gitu dan cerita kalau lukaku lebih banyak darinya. Tentu itu cara yang gak tepat, dari tulisan ini aku jadi kepikiran jika ketemu situasi serupa aku harus coba pakai trik dan cara yang berbeda.
Semoga namparnya pelan ya mas.
Karena kadang mereka nggak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Bisa jadi bawaan lingkungan yang ‘terlalu’ kompetitif. Hehehe.. 😁
“LU MAH MASIH MENDING.. LAH GUA…”, adalah kata-kata paling menyebalkan tiap kali lagi curhat. Bukannya dapet solusi, malah berasa direndahin wkwkwkwk.
Begitulah manusia, senantias memandang hidup sebagai kompetisi. Apapun aspek hidupnya senantiasa dijadikan sarana untuk beradu gengsi, meskipun terkadang pointless semata.
Btw pas baca, “makna dalam luka” kok aku langsung keingetannya sama Mbak Nik ya, hahahaha
mendang mending ini jadi jurus andalan beberapa orang kalau minta perhatian secara halus. Beberapa kenalanku malah kadang buat mengakhiri ‘dunia mendang mending’ cukup bilang. “Wah, mas/mbak hebat ya.” Hehehe..
Aku sendiri juga langsung klik sama tulisan mbak Nik kok. Ngingetin sama buku yang kubaca pertama kali punya Victor Frankl. ❤️
Lalu aku hening mencerna semua polah semut. Sebagai insan yang diberi peran mendengar, tersenyum getir kadang mendengar semua keluhnya atas peristiwa, tapi wajahku tak bisa memperlihatkan getir itu. Karena tugas sebagai pendengar memang cukup unik.
Berlomba atas luka memang fenomena yang terus menari dalam era butuh pengakuan. Buatku silahkan saja tetapi yang terpenting bagaimana luka itu tidak membuat yang lain terluka.
Terima kasih lagi untuk tulisan yang begitu dalam.
Dengar nama Focault jadi ingat zaman kuliah dulu, seingatku di kelas discourse analysis.
Mengenai adu luka kayaknya belum pernah yaa tapi pernahnya lagi curhat serius malah dibentak, dibilang elu tuh enak udah punya rumah blablabla..jadi speechless.
Sering sih.. aku juga pelaku.
Huhuhu.. rasanya suka malah jadi adu siapa yang paling susah. Tapi sejujurnya, aku memaknainya adalah dalam bentuk “Aku juga pernah mengalami hal yang sama”.
Bukan untuk merayakan kebersamaan duka, tetap lebih untuk saling menguatkan. Bahwa.. kita manusia, kita bisa mengeluh. Dan itu wajar atau manusiawi sekali.
Hanyaaa..
Kadang kita salah memilih kepada siapa kita mengeluh.
Aku setuju kalau ngeluhnya hanya sama Allaah.
Dan mungkin sesekali sama orang yang gak dikenal alias unknown. Karena mereka gakkan pernah mempermalukan kegagalan or kesedihan kita.
Kadang kita juga nggak sadar kok mbak, kalau pernah melakukan itu. Maksud hati pengen bilang ke yang punya masalah “kamu itu nggak sendiri” dan buat dia semangat lagi. Cuma kadang juga beberapa orang itu, kebablasan dengan adu ‘mendang-mendingnya’ yang bikin pencerita tidak nyaman.
Dan aku setuju banget curhat ke Tuhan lebih adem. 🙂
Dibuat cerita fabel begini jadi menohok.
Dan paling gak enak kalo udah bahas, “mendingan elu, daripada gua” Deehh itu mah, related beuddh sama kehidupan, bahkan dalam urusan perkomenan di medsos bahasan ini acap kali daku temukan huhu
Luka bukan hanya soal rasa sakit ya, tapi bagaimana kita memaknai dan menghadapinya. Untuk apa pamer jika tidak diobati terlebih dahulu. Emang hidup sekarang melelahkan banget. Semua berlomba demi mendapatkan pengakuan orang lain…
biasanya tanggapan kurang enak itu didapat dari orang yg lebih tua; berdasarkan pengalaman saya sih yaaaa… Mengeluh soal kerjaan atau tentang perlakukan semena2 seseorang, eh malah diremehkan , seolah si pendengar ini adalah org yg plg menderita sedunia. Mau curcol jadi minum panadol karena puyeng 🙂
Saya termasuk yang tidak biasa bercerita pada orang lain soal hal pribadi. Termasuk saat terluka. Karena yang paling memahami luka kita dan bisa menyembuhkan ya diri kita sendiri. Bercerita Luka pada orang lain malah mungkin akan membuat luka semakin parah bahkan bisa membuat luka baru
Sering terjadi sih hehehe. Mau curhat malah adu paling menderita. Kalau sudah gitu better aku jadi pendengar saja dan next time nggak akan curhat lagi sama orang seperti itu hehehe. Memang beberapa luka baiknya disimpan rapat-rapat. Boleh di ceritakan sama para ahlinya saja, agar tidak buang energi dan memberikan kelegaan hakiki.
Bahkan dulu saat pertama patah hati cielah. Tepatnya cinta tak bersambut, saya curhatnya pas shalat aja. Ternyata sembuhnya lebih cepat tanpa ada orang yang tau juga.
Tapi di masa sekarang emang banyak sih hal-hal yang perlu diceritakan bukan untuk Nemu solusi melainkan ingin didengarkan saja. Sesekali aja sih jangan keseringan takutnya orang bosan juga hehe.
waahhh aku sering kayak giniiiii *tutup muka pakai wajan*
jadi aku punya bestie yg dia tuh seriiinggg bangettt komplain hal² “sepele” dalam hidup.
Nah, biar doi ga merasa paling sial sedunia, biasanya aku crita klo hidupku beginiiii begituu
hmmm beklaahhh. akan aku ubah paradigmakuuuu
aku kan kecil itu tumbuh di lingkungan ekonomi bawah ya mbak.. kayak kelaparan, kdrt, dll itu udah jadi bagian kehidupanku dulu. Buat bisa sekolah itu sesuatu yang wow bgt, ga sedikit temenku yg sd ga lulus.
dan pas besar aku baru paham soal ini semua. Bahkan aku bisa dibilang ga inget masa kecilku kayak gimana.
baru sadar juga kalau ternyata luka-luka itu memang cukup dalam dan otakku katanya menghilangkan bagian-bagian yang menyakitkan itu. Aku cuma mau inget enak-enaknya saja sepertinya. tapi makin kesini kadang aku nangis gak jelas.. seperti sakit sama sesuatu tapi nggak inget apa yang bikin sakit.
#BigHugVirtual….
Kata psikolog itu begini, “kadang luka yang lebih berat itu mengendap dan yang bahkan bikin orang jadi lebih peka sama sedih.”
Dan orang-orang dengan kondisi terterntu seperti KDRT, tekanan finansial, tekanan pangan, sebetulnya butuh solusi, telinga dan tempat aman untuk bercerita. Harapanku semoga Mbak sudah menemukan tempat aman itu. :”)
kadang ada beberapa orang yang mana kalau kita curhat, ehh dia-nya malah menceritakan penderitaannya. Jadi nggak nemu solusi.
aku sendiri mungkin termasuk lebih banyak nyimpen masalah pribadi sendiri, sesekali aja curhat, itupun pilih pilih temen.
Terus kalau ada temen curhat, aku coba dengerin dulu permasalahannya, dan coba kasih pandangan solusi aja ke dia.
Setuju banget mbak…
Kadang cara taktisnya daripada curhat ke medsos atau ke orang tertentu yang malah tambah luka, mending pilih-pilih siapa yang mau diajak curhat. 😀
Aku setiap sharing luka ke orang yang ada makin menganga lukaku hahaha. Jadi udah wes gak mau lagi, cukup orang terdekat yang tahu, jadi manusia lain taunya kite happy2 aja hidupnya lancar.
Kadang malah orang tu gak merasa iba/ berempati yang ada malah nyukur2in, makin bikin nyesek.
Yg namanya luka atau kedukaan juga gak perlu dijadikan perlombaan seolah2 kita yang paling susah, padahal kalau di[ikir pakai logika nggak ada keuntungan sama sekali yang didapat hehe.
Nah itu dia mbak, kadang nggak sadar itu respondnya jadi malah mendang-mending dan bikin orang yang mau dapat solusi juga puyeng sama masalahnya. Aku suka kata-kata “kedukaan dijadikan perlombaan, apa untungnya?” 😀
Niatnya mau curhat, malah dapet komen nirempati seperti, kamu masih mending coba lihat aku atau orang disekitarmu. Mungkin niatnya baik, ingin kasih tahu kalau ngga cuma kamu aja yang menderita tapi masih banyak yang lebih menderita dibanding kamu. Tapi kan ngga begitu konsepnya, namanya curhat ya ingin didengerin aja sebenernya tanpa ngejudge apa-apa.
Memang tempat mengadu terbaik pada Sang Pencipta tanpa diketahui siapa-siapa, toh yang punya solusinya juga Yang Maha Kuasa.
Zaman now yang serba dibikinin konten ini kadang juga jengkel sendiri lihatnya, hal-hal yang ngga perlu dibikin konten atau status, buat validasi apa cobaa. Dikasih solusi juga toh yang bersangkutan sama aja.
Kadang kalau ada yang bercerita tentang kesedihannya, saya juga suka share pengalaman serupa juga sih. Bukan buat adu nasib, justru biar yang cerita merasa ada teman senasib. Hehe.. Tapi tetep validasi perasaannya itu penting dan bukan malah kebalikannya, awalnya dia yang mau curhat malah kita yang lebih banyak ngomong panjang x lebar. Heu..
Banyaaak memang orang beginiiiiii 😂. Dan jujur aku ga suka. Tp kalo lagi sial nemuin tipe orang yg suka pamer penderitaan gini, aku dengerin ajalah mba. Males adu2an 😂🤭.
Aku sukaaa dengan Kata2 di atas, “Jika kau terluka, bukan seberapa dalam luka derita yang kau terima. Tapi, bagaimana caramu merespon luka itu,”
Naah ini beneeer. Luka, cobaan, penderitaan, pada akhirnya yg penting bagaimana cara kita utk handle itu semua. Bukan malah dijual , dibuat perlombaan mana yg paling sedih, diundang ke podcast utk ceritain luka nya… Muak sih Ama yg begini. Kalo dalam suatu perlombaan nyanyi, ada peserta yg jual kesedihan, fix , aku ga bakal pilih dia.
Serius ada ya mbak sampai yang jual kesedihan?? Jujur, aku jarang nonton ajang pencarian bakat, karena kadang terlalu drama dalam penjuriannya. 😀
Tapi emang kadang, kalau udah mewek-mewek gitu jadi mempertanyakan lagi “nangis tulus” atau …. 🙁
İtulah kenapa kalo mendengarkan cerita orang tidak sebegitu antusias. Yah B aja lah, nanti malah adu nasib, kalo nggak gitu adu pencapaian. Rasanya capek!! Mending cerita ke suami aja atau cerita ke blog pribadi.
25 Responses